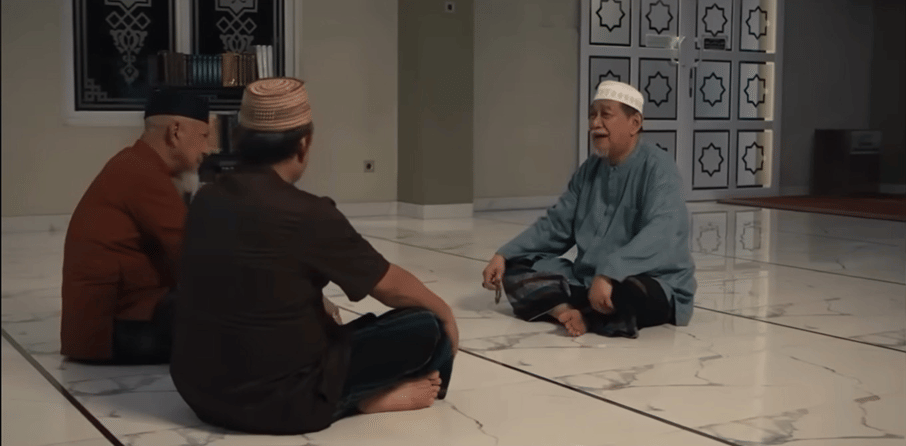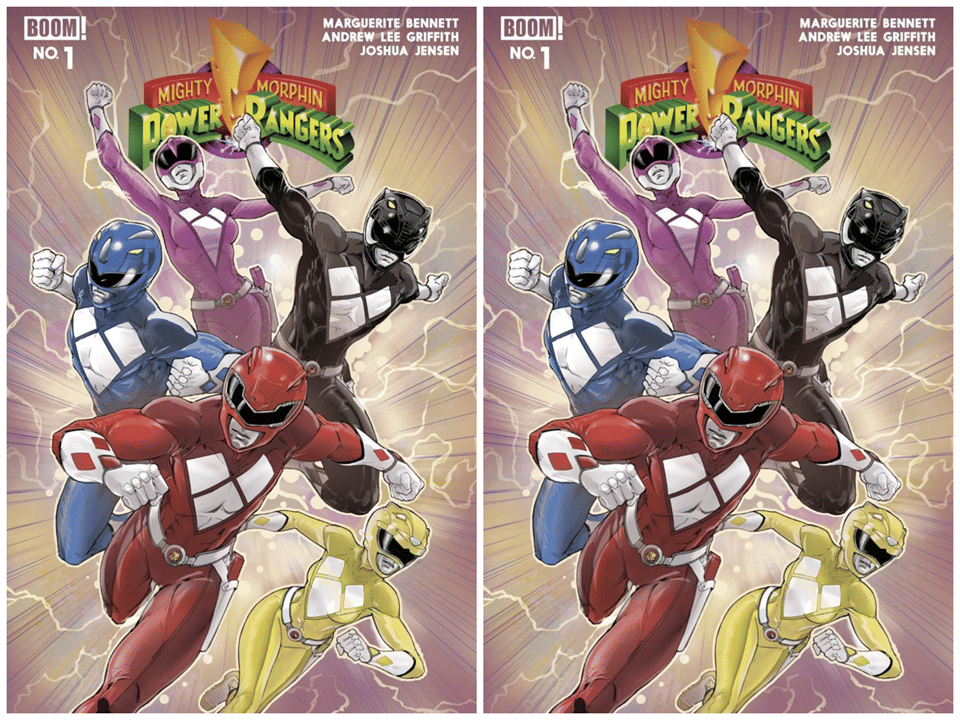GENRE: Drama
ACTORS: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem
DIRECTOR: Joseph Kosinski
RELEASE DATE: 25 Juni 2025
RATING: 3/5
Penilaian Film: F1, Ketika Mesin, Ego, dan Emosi Berpacu di Lintasan yang Sama

Mentor Tua, Murid Egois, dan Tim yang Nyaris Bangkrut
Sinematografi Juara, Teknologi Real-Time, dan Musik yang Menggedor
Kate McKenna dan Nafas Emosional yang Dibutuhkan Film Ini
Joseph Kosinski membawa kita masuk ke dunia Formula One lewat F1, sebuah film yang memadukan teknologi modern, nostalgia gaya lama, dan para karakter yang mencoba menemukan kembali jati diri mereka di balik helm balap. Dengan bintang utama Brad Pitt dan Damson Idris, serta visual spektakuler hasil tangan dingin Claudio Miranda, film ini tampil menggoda secara sinematik. Tapi di balik deru mesin dan kecepatan yang nyaris hipnotik, ada sisi naratif yang kadang masih kurang percaya diri.
1. Mentor Tua, Murid Egois, dan Tim yang Nyaris Bangkrut

Plot F1 bukan hal yang benar-benar baru. Brad Pitt memerankan Sonny Hayes, mantan pembalap Formula One yang dulu dikenal sebagai "fenomena lintasan", tetapi kariernya hancur karena kecelakaan dan ego yang tak bisa dikendalikan. Bertahun-tahun kemudian, Sonny hidup sebagai semacam pembalap keliling, mengemudi mobil apa pun. Mulai dari mobil sport hingga taksi, hanya demi sensasi adrenalin.
Kehidupannya berubah saat Ruben Cervantes (Javier Bardem), teman lama sekaligus manajer tim balap APX yang sedang sekarat secara finansial, menawarkannya kursi balap untuk menyelamatkan citra tim. Sonny awalnya menolak, seperti yang diharapkan dari klise film olahraga manapun, lalu tentu saja setuju, memulai kisah kembalinya "sang veteran bermasalah" ke lintasan elit.
Di sisi lain, Damson Idris berperan sebagai Noah Pearce, pembalap muda yang haus sorotan dan merasa tidak membutuhkan siapa pun. Kehadiran Sonny dianggap sebagai gangguan: simbol dari masa lalu yang seharusnya sudah mati. Interaksi mereka berjalan dari permusuhan, saling meremehkan, lalu pelan-pelan bertransformasi menjadi hubungan mentor–murid yang cukup emosional, meski sayangnya tidak pernah benar-benar mendalam.
Narasi Sonny sebagai "pembalap lama yang menolak pensiun" sebenarnya berpeluang memberi nuansa eksistensial dan reflektif. Tapi alih-alih merenungkan makna kegagalan dan umur, film ini memilih jalur aman dengan konflik-kompetisi yang terlalu cepat berdamai. Noah sendiri, sebagai karakter, lebih terasa sebagai simbol generasi muda yang terlalu dimanja ketenaran ketimbang pribadi yang berkembang nyata.
2. Sinematografi Juara, Teknologi Real-Time, dan Musik yang Menggedor

Kalau bicara kekuatan utama film F1, jawabannya ada pada visual dan atmosfer balapannya. Joseph Kosinski jelas tahu bagaimana cara membangun dunia yang memikat secara visual. Berbekal pengalaman menggarap Top Gun: Maverick, dia kembali bekerja sama dengan sinematografer Claudio Miranda dan hasilnya luar biasa.
Setiap adegan balapan terasa seperti dilihat langsung dari dalam kokpit mobil. Kamera berputar di sekitar helm pembalap, meluncur di lintasan, menggetarkan kursi bioskop lewat kecepatan yang direkam dengan intensitas tinggi. Tidak ada CGI berlebihan; banyak adegan memang direkam langsung dari sirkuit Formula One sungguhan seperti Silverstone dan Spa.
Lalu ada Hans Zimmer, yang lagi-lagi tahu cara mengaduk-aduk jantung penonton lewat musik berdentum elektronik dan komposisi yang sinkron dengan momen balapan. Score Zimmer tidak hanya sebagai pengiring, tapi sebagai alat untuk menambah ketegangan dan irama setiap adegan balap. Rasanya seperti video game premium dengan ketegangan maksimal – tapi dalam kemasan film festival.
Film ini juga terasa sangat "disahkan" oleh dunia F1: dari desain mobil, bahasa teknis yang digunakan di pit stop, hingga bagaimana sistem telemetry dan data real-time ditampilkan di layar monitor tim. Buat penonton awam, ini bisa jadi membingungkan. Tapi buat pecinta Formula One, ini adalah sajian yang sangat nikmat dan mungkin satu-satunya film yang benar-benar terasa seperti dokumentasi resmi dunia balap profesional.
3. Kate McKenna dan Nafas Emosional yang Dibutuhkan Film Ini

Di dunia yang penuh testosteron, adrenalin, dan ego, kehadiran Kate McKenna (diperankan dengan brilian oleh Kerry Condon) menjadi jembatan yang sangat penting. Ia adalah kepala teknis aerodinamika tim APX, sosok yang tidak hanya pintar dan teknikal, tapi juga punya insting emosional yang kuat. Dalam banyak hal, dialah yang membuat tim ini tidak meledak dari dalam.
Kerry Condon tampil sangat natural. Karakter Kate punya chemistry yang mengejutkan dengan Sonny, bukan dalam arti romantis, tapi lebih seperti dua manusia yang saling mengerti satu sama lain di tengah dunia yang keras dan bising. Condon tak banyak mendapat screen time, tapi setiap kali ia muncul, film ini terasa lebih hangat, lebih manusiawi.
Peran perempuan dalam film balap sering kali hanya sebagai pemanis atau pendukung tokoh utama laki-laki. Tapi Kate punya agensinya sendiri. Ia bukan cheerleader di pit stop. Ia tahu seluk-beluk mobil, berdebat soal spesifikasi teknis, dan bisa memarahi pembalap seperti bos sejati. Ini adalah bentuk representasi yang patut dicontoh oleh film olahraga lainnya.
4. Terlalu Banyak Penjelasan, Terlalu Sedikit Percaya Diri

Masalah terbesar F1 adalah ketakutannya untuk mempercayakan emosi dan ketegangan pada visual. Hampir setiap momen dramatis, baik di lintasan maupun di luar, diiringi oleh narasi komentator, dialog yang terlalu ekspositori, atau musik yang terus-menerus mengarahkan emosi penonton. Alih-alih membiarkan penonton merasakan sesuatu, film ini seperti berkata, "Hei, kamu harus merasa tegang sekarang!"
Dalam adegan balap, ini menjadi lebih terasa. Komentator TV menjelaskan posisi, strategi, kondisi ban, dan hal-hal teknis lain yang sebenarnya bisa saja disampaikan lewat ekspresi wajah, reaksi kru tim, atau bahkan keheningan. Bandingkan dengan Rush (2013) atau Ford v Ferrari (2019), di mana momen terbaik justru muncul saat suara mesin adalah satu-satunya dialog.
Karakter Sonny pun menjadi korban dari kebiasaan film ini untuk terlalu banyak menjelaskan. Kita diberi tahu berulang kali bahwa dia tidak peduli pada uang, tidak mau piala, hanya peduli pada kecepatan. Tapi semua itu jadi tidak terlalu menggugah karena kita tak pernah benar-benar diajak menyelam ke dalam trauma dan rasa bersalahnya. Sonny adalah karakter yang menarik, tapi tidak pernah diberi waktu untuk benar-benar diam dan membiarkan kita mengerti tanpa kata.
4. Kesimpulan

F1 adalah film yang indah secara visual, cepat secara ritme, dan punya semangat kompetisi yang membara. Tapi seperti mobil balap yang kecepatannya melebihi kontrol, film ini kadang terlalu sibuk memamerkan teknologi dan gaya, sampai lupa memberi ruang bagi keheningan, kerentanan, dan konflik batin karakter.
Brad Pitt tetap karismatik, Damson Idris menjanjikan, dan Kerry Condon mencuri hati, tapi kisah mereka berputar-putar di sirkuit yang terlalu aman. Film ini bisa jadi favorit penggemar F1 karena otentisitas teknisnya, tapi buat penonton yang mencari drama mendalam dan cerita yang menyentuh hati, F1 mungkin hanya terasa seperti putaran pemanasan.