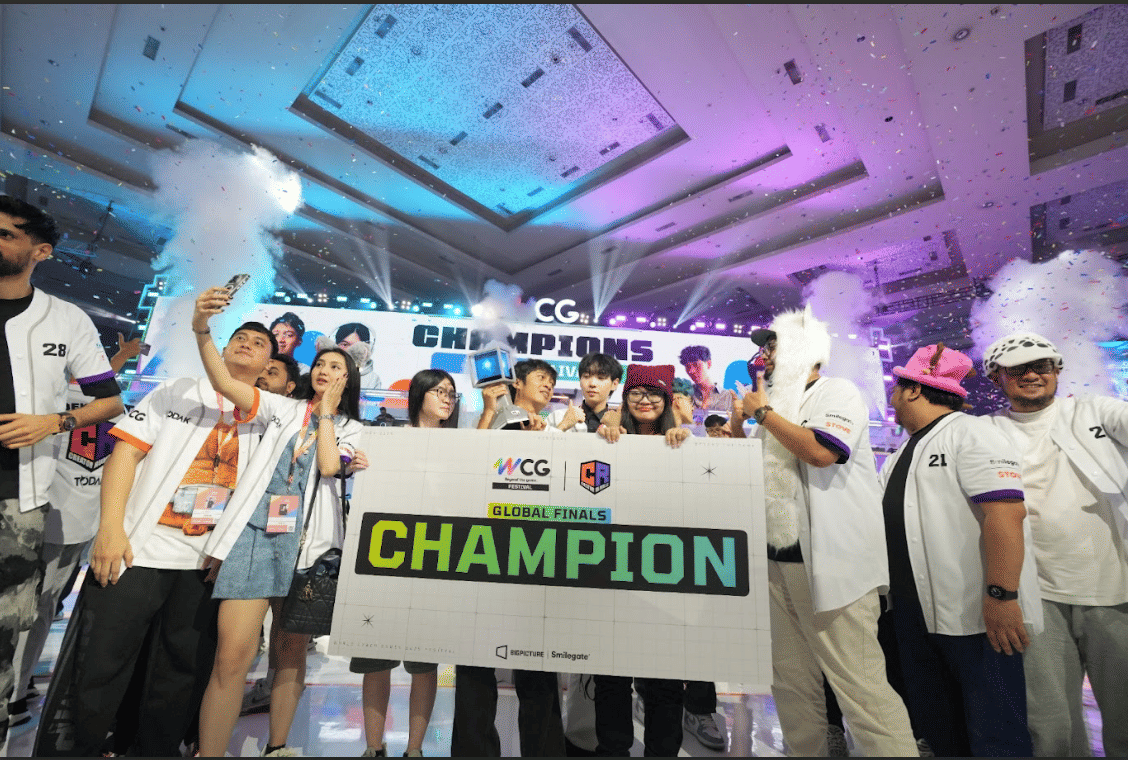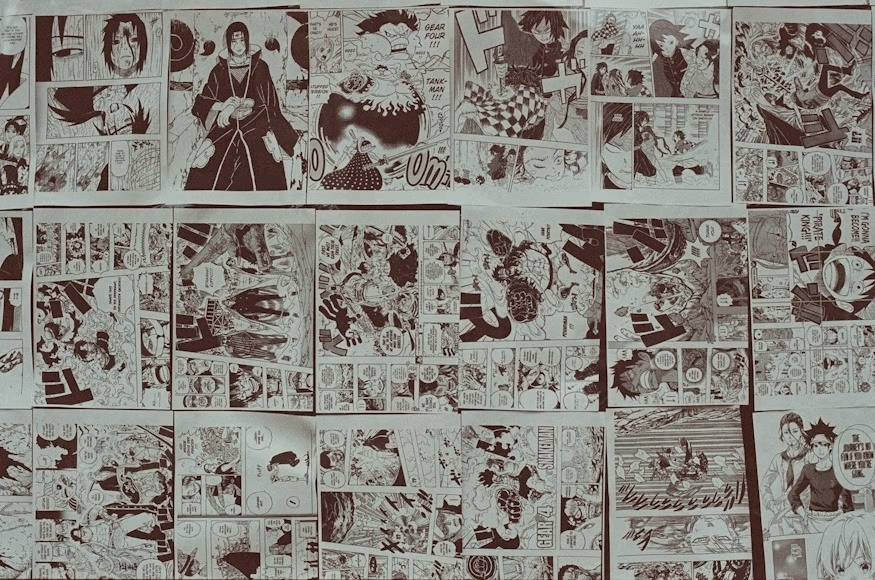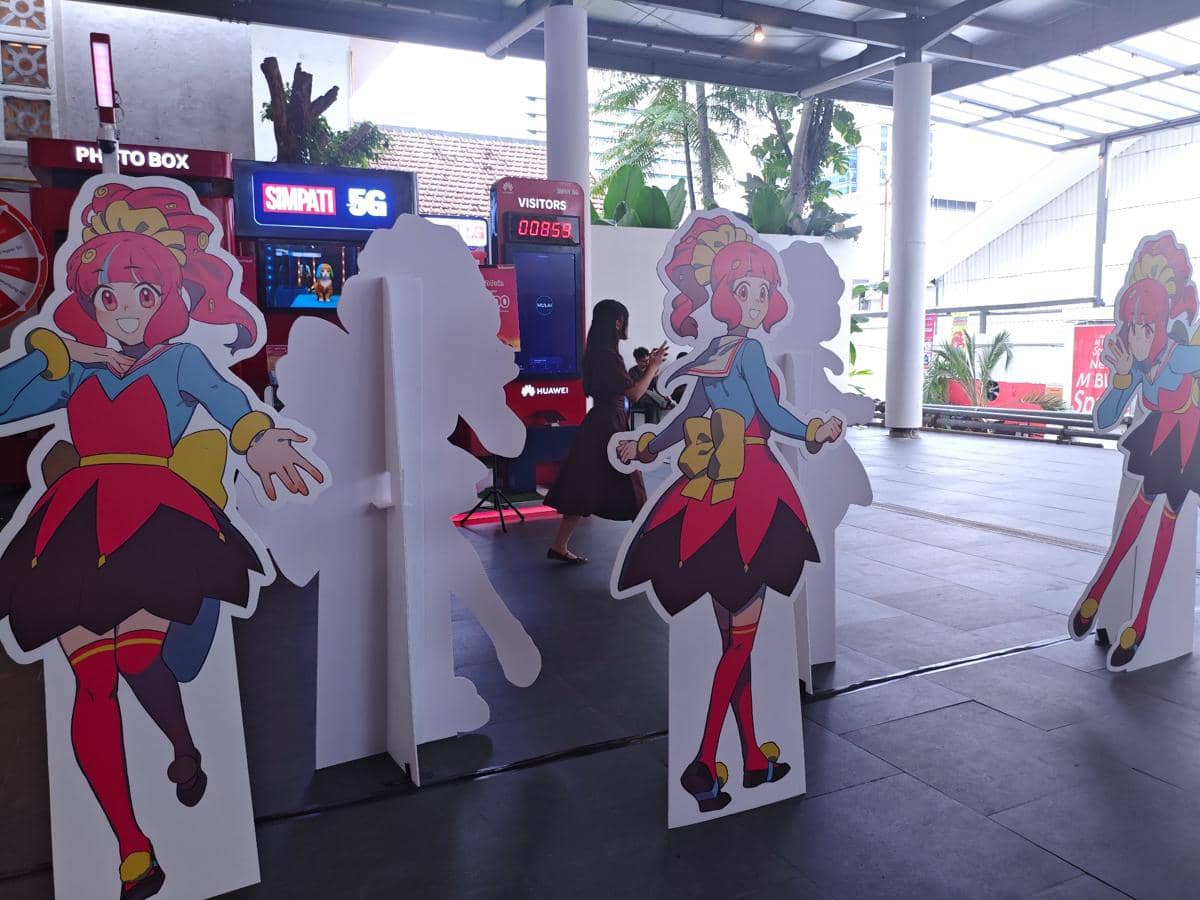Review Lady Bird: Menjadi Gadis Degil di Kota Udik

Sinopsis
mengikuti kisah Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan), seorang gadis degil alias kepala batu. Ia menganggap kehidupan di Sacramento, ibukota negara bagian California itu udik dan kampungan. Lady Bird—nama panggilan yang ia bikin sendiri—berkali-kali mengutarakan keinginannya kuliah di kota “budaya” di pesisir timur Amerika, seperti New York, New Hampshire, dan Connecticut.
Namun kelakuan degilnya itu harus berhadapan dengan ibunya (Laurie Metcalf) yang juga berperangai keras. Meskipun selalu bertengkar, keduanya saling perhatian. Lady Bird juga menjalani kehidupan SMA-nya di sekolah Katolik yang konservatif.
Tentang Merantau dan Menjadi Merdeka
Jika kamu seorang remaja
kuliahan
,
Lady Bird
adalah film yang akan kamu sebut jika ada orang bertanya siapa dirimu. Ia justru bukan memberi jawaban atas pertanyaan tersebut, melainkan menggambarkan secara jujur kehidupan remaja yang ingin merantau.
Ia sangat dekat dengan kehidupan remaja, seperti soal mimpi keluar dari kampung halaman yang membosankan, soal siapa teman terbaik, hingga yang paling utama namun jarang diangkat film-film remaja: hubungan akrab putri dengan ibunya.
Sedari awal, penonton langsung diperlihatkan betapa dekatnya ia dengan sang ibu. Lalu, sekonyong-konyong keduanya ribut hingga berujung pada kelakuan Lady Bird melempar dirinya sendiri keluar dari mobil yang sedang melaju.

Lady Bird dan ibunya dalam mobil. Sumber: Variety[/caption]
Adegan itu singkat, tetapi cukup mampu merangkum bagaimana hubungannya dengan sang Ibu, Marion. Awalnya
marahan
, lalu sedetik kemudian
baikan
. Saya punya adik dan ibu yang seperti ini juga, sama-sama saling kesal satu sama lain karena perbedaan pandangan, tapi jauh di dalam hati, sayang betul.
Lady Bird adalah gadis dengan perangai degil. Entah makanan apa yang ia makan waktu kecil sehingga membuatnya jadi super eksentrik seperti itu. Ia rela menyelipkan majalah dalam bajunya gara-gara enggak dibelikan Marion saat di swalayan. Saat orang-orang ikut audisi teater dengan pakaian sekolah, ia justru datang dengan seragam dan riasan sendiri.
“Kamu terlahir sebagai pemain sandirawa,” kata gurunya setelah melihat tabiat Lady Bird yang gemar cari perhatian.
Tidak hanya buat gadis-gadis (terutama hubungannya dengan ibu),
Lady Bird
juga dengan mudah
relate
pada gender lain. Gadis pemberontak ini sangat benci sekali pada Sacramento yang menurutnya kampungan. Jika ia tinggal lebih lama, ia sudah bisa memprediksi masa depannya sendiri: masuk universitas negeri, 30 menit naik mobil dari rumah; lalu mengacau sedikit dan masuk penjara sebentar; lalu menjadi mahasiswa tak berprestasi; hingga kemudian hidup pas-pasan menjadi kasir swalayan sampir akhir hayat.
Mengenai Sacramento yang udik dan New York yang “berbudaya” ini, saya merasa
relate
sekali dengan itu. Pematangsiantar dan Medan—tempat lahir dan tinggal—ini sangat membosankan dan “soul-killing” dibandingkan kota kreatif Jakarta dan kota kaya budaya seperti Yogyakarta. Di sana, orang-orang tampak berbuat sesuatu yang
bermakna
, dibanding Medan yang
gini-gini aja
. Saya yakin orang-orang yang merantau dari kampung halamannya juga merasakan hal serupa.
Soal merantau dalam film ini bukan hanya soal kota, tetapi manusia-manusia yang tinggal di dalamnya. Lady Bird merasa manusia-manusia Sacramento kaku dan sulit berkembang. Hal ini digambarkan lewat lingkungan sekolahnya yang konservatif, yakni sekolah Katolik. Berdansa berdua saja harus dibatasi 15 cm untuk “memberi tempat buat Roh Kudus”. Seks adalah pembicaraan yang canggung dan kegiatan seninya
jadoel
.

Lady Bird dan Jules, sahabatnya.[/caption]
Bandingkan dengan New York, saat Lady Bird berhasil merantau. Di sana, mahasiswa pertama yang ia kenal mengaku tak mengakui Tuhan, semuanya
bebas
dan
merdeka
dengan tubuh masing-masing.
Namun, Lady Bird merasa ada yang hilang. Saya juga merasa ada hal yang hilang ketika berpergian ke kota besar lain. New York tiba-tiba jadi tak ramah. Jalanannya ramai seperti biasa, tetapi ia kesepian. Saat baru sadar dari mabuknya, ia mengunjungi gereja, mendengarkan nyanyian merdu di dalamnya, lalu ia kangen rumah dan ibu, hingga air matanya pun meleleh.
Film
Lady Bird
berbicara lebih dalam daripada menertawakan kelakuan gadis degil bernama Lady Bird. Ia masuk ke dalam relung hati mereka yang berhasil
relate
, lalu memompa emosi dari sana. Ia mengikuti lebih dekat tumbuh kembang sebagai remaja, hubungan cinta dan benci pada ibu, dan soal merantau itu.

Greta Gerwig (kanan) bersama Saoirse Ronan dalam set film Lady Bird. Sumber: Rolling Stone[/caption]
Lady Bird
lucu dan tragis di saat bersamaan. Di tangan sutradara yang berbeda,
Lady Bird
barangkali tidak akan se-sensitif dan se-personal ini.
Greta Gerwig
dalam debutnya sebagai sutradara berhasil menyampaikan kisah remaja ini dengan
powerful
.
Performa akting aktris Saoirse Ronan juga tidak boleh dilupakan. Aktris peraih tiga nominasi Oscar ini (
Atonement, Brooklyn,
dan film ini) mampu membuat Christine McPherson si Degil hidup dan bernyawa. Oh, tidak lupa juga Laurie Metcalf sebagai ibu Lady Bird. Jika bukan karena Metcalf, rasanya adegan saat Marion menangis di mobil tidak akan mampu membuat badan bergidik dan mata
banjir
.
“Kamu sepertinya cinta sama Sacramento,” kata biarawati yang mengurus sekolah Katolik, setelah membaca esai Lady Bird.
“Ah, masa?”
“Kamu menulis soal Sacramento dengan rasa sayang dan peduli.”
“Aku cuma mendespripsikannya saja.”
“Sepertinya kamu memang cinta.”
“Yah, aku orangnya memang suka memperhatikan segala sesuatu.”
“Bukankah menurutmu keduanya berhubungan? Cinta dan perhatian?”
Sacramento sama halnya seperti Marion bagi Lady Bird. Kelihatannya saja ia tak suka, tetapi hal inilah yang ada dalam Sacramento dan Marion, namun tidak ia temukan ketika berada di New York: cinta.
Diedit oleh Fachrul Razi