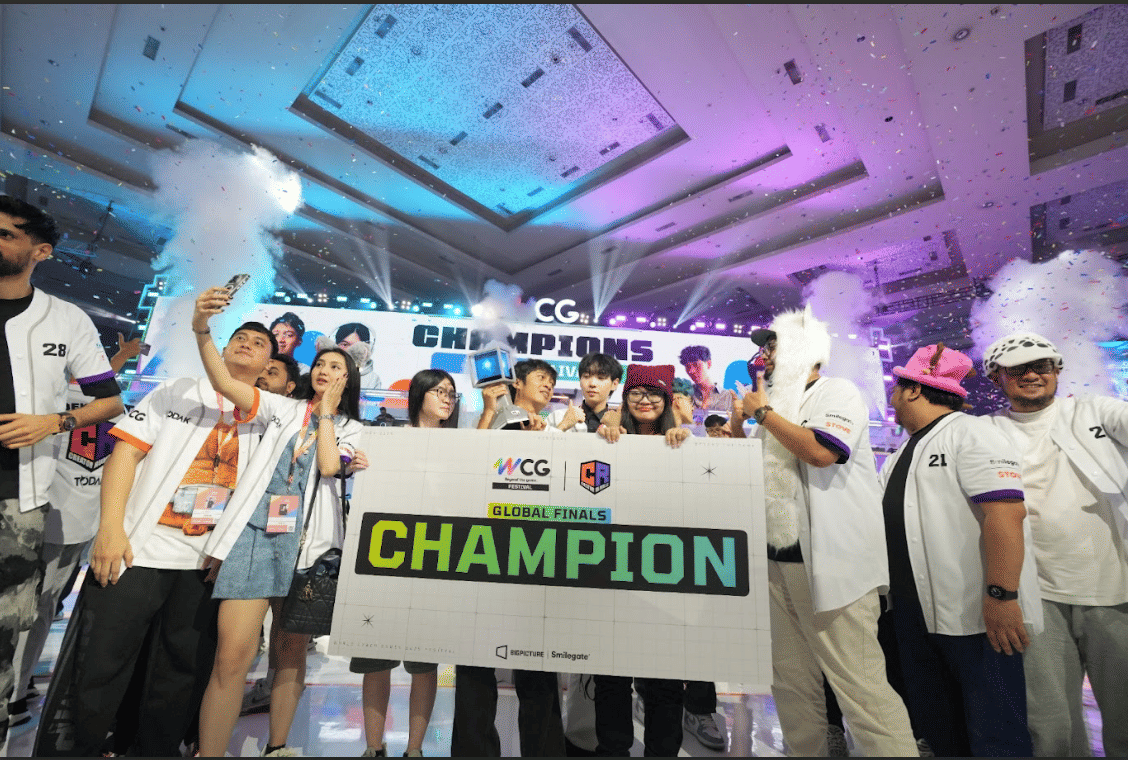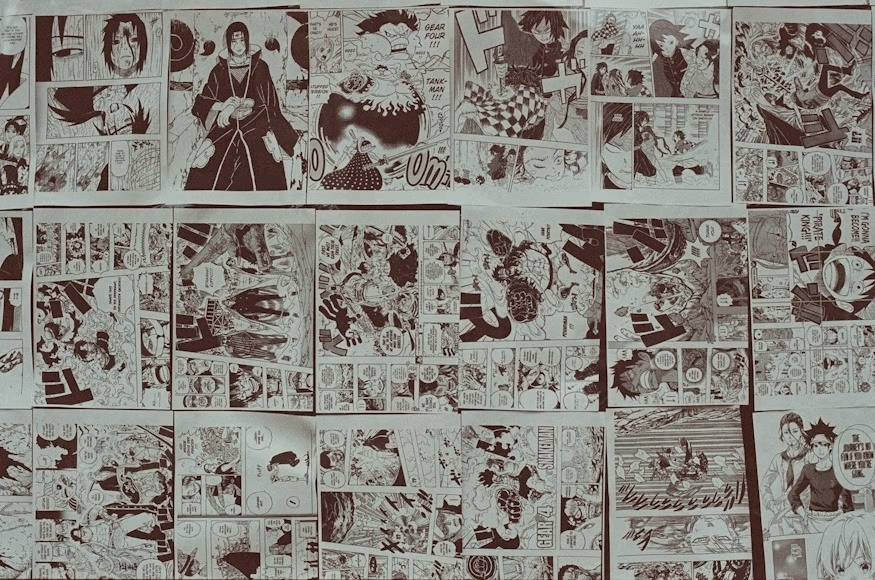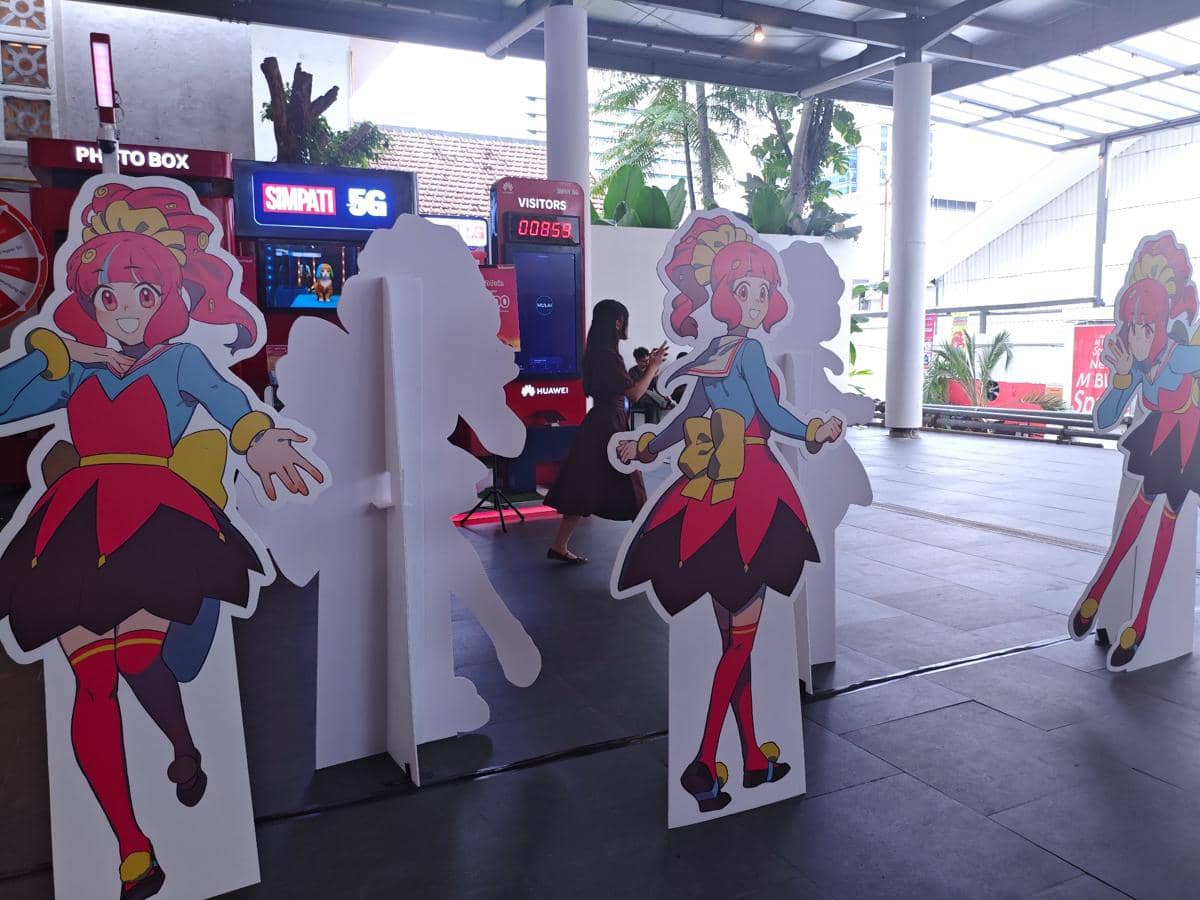aku ingin mencintaimu dengan sederhana:dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya abu
Review Hujan Bulan Juni: Perkawinan Film dan Puisi

Film ini berusaha mengawinkan narasi film yang tersurat dengan puisi Sapardi Djoko Damono yang tersirat. Simak hasilnya lewat review Hujan Bulan Juni berikut ini.
Itulah sebait puisi Aku Ingin oleh pujangga gaek Sapardi Djoko Damono. Puisi yang ditulisnya tahun 1989 ini kemudian banyak memperkenalkan nama Sapardi kepada orang awam. Puisi-puisi Sapardi sangat indah dan banyak berbicara tentang cinta serta Tuhan. Barangkali karena itulah karyanya digemari banyak orang.
[duniaku_baca_juga]
Sejak masih SMA tahun 1957, Sapardi sudah mulai menulis. Puisi-puisinya dari tahun 1959 sampai 1994 kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku berjudul Hujan Bulan Juni yang terbit tahun 1994.
Banyak orang sudah mengadaptasi puisi Sapardi, termasuk musikalisasi. Kali ini di tahun 2017, puisi-puisinya divisualisasi lewat film berjudul sama yang sedang tayang sekarang.
Sebelum masuk ke review Hujan Bulan Juni, ada baiknya baca sinopsis di bawah ini terlebih dahulu.
Sinopsis
Suatu hari, hiduplah Sarwono (Adipati Dolken) dan Pingkan (Velove Vexia), dua sejoli yang menghabiskan hidupnya di lingkungan universitas. Sarwono adalah akademisi antropologi dan Pingkan seorang dosen muda yang dapat kesempatan kuliah di Jepang selama 2 tahun.
Takut kesepian dan khawatir kekasihnya direbut Katsuo (Kaukaro Kakimoto), Sarwomo mengajak Pingkan untuk menemaninya bertugas ke Manado. Di sanalah Pingkan bertemu dengan keluarga besar dari ayahnya, termasuk sepupu Ben (Baim Wong), yang membombardirnya dengan sejuta pertanyaan karena Sarwono seorang Jawa.
Bagaimanakah keduanya bisa bertahan? Simak review Hujan Bulan Juni di bawah ini.
Cinta yang Dewasa

Film Hujan Bulan Juni bukanlah tipikal konflik percintaan yang cengeng seperti film-film remaja pada umumnya. Ia terlihat lebih dewasa, terutama jika kita melihat cara Sarwono dan Pingkan memaknai hubungan mereka.
Keduanya sering membahas soal ketakutan jikalau salah satu dari mereka direbut orang. Tidak ada acara ngambekan karena yang kurang perhatian atau acara banting-banting piring. Ada masalah kompleks tentang perbedaan suku dan keyakinan dalam hubungan mereka.
Sarwono adalah orang Jawa-Islam dari Solo. Kulitnya yang cokelat dan logatnya yang Boso Jowo mudah dikenali. Dan hal tersebut menjadi bahan perbincangan keluarga Pingkan yang seorang keturunan Minahasa-Kristen.
Tapi beginilah indikator kedewasaan film ini: masing-masing dari Sarwono dan Pingkan tidak buru-buru mewek dan masuk mode melodramatis ketika dihadapkan pada situasi rumit seperti itu.

Ketika ditanya Ben soal kemungkinan memakai jilbab, Pingkan santai-santai saja. Ini menunjukkan bahwa baik Sarwono maupun Pingkan sudah melihat hal yang lebih besar daripada sekadar latar belakang.
“Di Manado enggak ada bandara, ya,” ujar Sarwono pada Ben, dengan bandara sebagai kiasan atas modernisasi. Padahal mereka berdua habis check in mau naik pesawat.
Hujan Bulan Juni memilih untuk menyalurkan emosinya lewat analogi bait-bait sajak dari Sapardi Djoko Damono. Maka atas pilihan ini, sutradara Hestu Saputra (Cinta Tapi Beda, Air Mata Surga) dan penulis naskah Titien Wattimena (Mengejar Matahari, Salawaku) punya beban untuk mengawinkan medium film dengan puisi.
Dan ternyata itu tidak berjalan begitu baik.
Alih bentuk dari puisi menjadi film dalam Hujan Bulan Juni tak berjalan lancar. Simak mengapa dalam review Hujan Bulan Juni selanjutnya di halaman sebelah!
Gagalnya Perkawinan Film dan Puisi

Puisi-puisi Sapardi memang indah dengan olah kata mengagumkan, tetapi pembaca (dan penonton) butuh waktu untuk diberi kesempatan berimajinasi dan menginterpretasikan makna puisi tersebut sendiri.
Sementara film ini menarasikan ceritanya secara tersurat, yang berarti banyak penjelasan gamblang tentang apa yang sedang terjadi.
Misalnya, saat Katsuo melangkah menjauhi Pingkan, muncul voiceover suara Velove yang mengatakan apa yang sedang terjadi antara dia dan Katsuo. Ini membuat penonton merasa tak perlu membuat interpretasi sendiri, sebab sudah dikatakan langsung oleh film.
Sementara itu puisi Sapardi:
tak ada yang lebih tabahdari hujan bulan juni
dirahasiakannya rintik rindunya
kepada pohon berbunga itu
Penuh dengan kiasan dan multitafsir.
Celakanya, karena perselisihan antara cara bercerita film dan puisi ini digabungkan menjadi satu, maka keduanya berebut atensi penonton. Keindahan puisi Sapardi datang dengan kesulitan penonton mencerna maknanya dalam sekilas. Apalagi film Hujan Bulan Juni tak memberi waktu banyak agar penonton dapat membaca teks puisi yang ternukil di layar perak.
Maka menonton cenderung lebih memilih yang mudah-mudah saja, yaitu sekadar menikmati keindahan puisi Sapardi, seakbar apa pun makna di baliknya.
Lalu, bagaimana caranya agar film dan puisi dapat kawin? Dengan visualisasi puisi. Visualisasi puisi memungkinkan Hujan Bulan Juni tak perlu berbicara banyak, lupakan voiceover apa yang sedang terjadi, dan bermainlah dengan gambar.

Seperti halnya kata, gambar juga bisa puitis. Dan itulah yang tak tergambar dalam Hujan Bulan Juni. Banyak dari puisi Sapardi hanya sekadar menjadi teks yang tertempel di layar, dengan latar belakang yang di-blur.
Hestu Saputra dan penata gambar Faozan Rizal bisa bereksperimen dengan visual yang menggambarkan makna puisi yang sedang dirapal.
Ada beberapa kali film ini bereksperimen dengan gambar-gambar yang puitis, seperti ketika mereka di Manado, Pingkan bermimpi berada di puncak gunung bersalju bersama seorang geisha yang menari-nari. Tapi ini tak dilakukan ketika film mulai memasuki jadwal membaca puisi—yang semakin ke belakang semakin terlihat repetitif.
Pilihan ini sebenarnya wajar jika mengingat film ini adalah film komersil dan keputusan untuk condong ke arah film yang puitis justru akan menyingkirkan mayoritas penonton film Indonesia.

Padahal, tata gambar oleh Rizal menciptakan banyak lansekap indah, terutama saat film memasuki cerita di Manado. Ada banyak situs-situs yang indah ditangkap mata lensa, seperti Patung Yesus Memberkati, Danau Linow, hingga Pantai Likupang.
Semuanya diolah tanpa membuatnya terlihat dieksploitasi habis-habisan (yes i’m talking to you, Trinity, the Nekad Traveler). Tapi yang paling indah adalah pencahayaan film ini. Berbagai warna cahaya dari lampu pendar dimanfaatkan, seperti merah dan biru di Kota Manado dan oranye dan hijau ketika mereka mampir di masjid. Elok sekali.
Usaha untuk mengawinkan film dan puisi ini sangat terbantu oleh penampilan para aktornya. Adipati Dolken, yang baru-baru ini terlihat creepy jika kamu telah menonton Posesif, berhasil memberi aura kaku, jadul, namun berpendirian teguh ke dalam tokoh Sarwono. Sementara itu pasangannya, Velove Vexia mengimbanginya dengan energi dan keceriaan ke dalam diri Pingkan.
[read_more id="341237"]

Penampilan paling memuaskan tak disangka-sangka datang dari Baim Wong, yang memerankan tokoh Ben. Ia yang selama ini dikenal lewat berbagai perannya di sinetron dengan sangat baik menyuntikkan kehidupan ke dalam karakter Ben. Logat Minahasanya terdengar sangat natural dan bahasa tubuhnya yang energetik berhasil membuat penonton tertawa.
[read_more id="343872"]
Sebagai kesimpulan dari review Hujan Bulan Juni ini adalah, bahwa film ini berupaya untuk mengawinkan medium film dan literatur (puisi). Sayangnya kedua unsur tersebut terlalu keras kepala, dan medium film tak mampu sinkron dengan puisi sehingga meninggalkan sedikit sekali kesan buat penonton, apalagi endingnya diakhiri dengan terburu-buru.
Diedit oleh Doni Jaelani